KOMPAS, 30 April 2004
Oleh: Agus Purwanto*)
Kasus pangkat dan golongan Dr. Terry Mart di jurusan fisika UI jelas kalah populer dari
kasus pemilu dan capres RI, meskipun demikian tetap sangat menarik untuk terus
diangkat. Pasalnya, kasus Terry Mart adalah potret buram dunia ilmu di negeri ini.
Sementara tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan suatu negeri juga berbanding dengan
kemajuan dunia ilmu.
Publikasi Terry Mart di jurnal internasional bias dilihat misalnya di http://xxx.lanl.gov
milik Los Alamos National Laoratory. Ada sekitar empat puluh published paper Terry
Mart bersama koleganya di dalam dan luar negeri. Dengan reputasi tersebut, dia adalah
satu dari amat sangat sedikit the real scientists yang kita miliki. Namun masa kerjanya
yang lebih dari sepuluh tahun dan reputasinya memang tidak serta merta membuatnya
dihargai. Sampai saat ini ia masih golongan 3A, golongannya sepuluh tahun lalu.
Seperti disinggung oleh Liek Wilardjo (Kompas, 9/3/2004) ada prosedur promosi yang
salah di fisika UI khususnya dan Indonesia umumnya. Keruwetan birokrasi, standar
yang tidak sama dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepedulian dan kesadaran
pejabat atau atasan merupakan sebabnya.
Keruwetan birokrasi telah menjadi rahasia umum dan terjadi di mana-mana. Birokrasi
kita berpijak pada filosofi jahiliyah “bila dapat dipersulit mengapa harus dipermudah”.
Standar formal memang sama tetapi standar moral berbeda dan sangat bergantung pada
latar belakang kumpulan individu di dalamnya. Staf senior fisika UI Dr. Na Peng Bo
merasa malu untuk menjadi dan mendapat gelar guru besar. Sedangkan satu-satunya
kosmolog kita Jorga Ibrahim, DSc sampai pensiun juga tidak menyandang gelar
tersebut. Sementara di tempat lain gelar ini diperebutkan oleh orang-orang yang relatif
sepi dari prestasi ilmiah.
Standar moral ini memang kembali kepada sikap dan pilihan individual yang harus
dihormati oleh siapapun sepanjang individu bersangkutan menerima konsekwensi
pilihannya. Ada seorang staf senior yang memperoleh gelar doktornya dari Amerika
belakangan ini rajin mengurusi promosi guru besar setelah tahu salah seorang muridnya
kini telah menjadi professor. Inilah contoh konsekwensi dari pilihan. Menjadi guru
besar bukan karena penghayatan tata nilai dan standar reputasi tetapi karena
pertimbangan subyektif dan lokal.
Masyarakat umum sangat silau pada gelar professor meskipun mereka tidak tahu
menahu kualitas serta jenis keprofesoran seseorang. Adalah fakta, bahwa profesor –
misalnya- di jurusan fisika seringkali sejatinya bukanlah guru besar di bidang fisika.
Namun demikian, seorang professor akan diperlakukan sangat istimewa bila berobat di
rumah sakit. Ia juga bisa mendapat honor sampai lima kali lipat dibanding sebelum
menjadi professor bila diundang ceramah. Jadi gelar professor memberi keuntungan
material yang lumayan.
Mungkin yang perlu kita soal adalah kepedulian pejabat terkait atas proses promosi. Di
salah satu fakultas di UGM proses kenaikan pangkat berjalan otomatis tanpa harus
mengurus sendiri. Para staf tinggal menjalankan tugas mengajar dan meneliti. Suatu
ketika mereka diberi tahu bahwa per tanggal sekian mereka telah naik jenjang. Jurusan
mereka telah membuat tim untuk proses kenaikan pangkat. Proses otomatis ini tidak
berarti mengurangi nilai atau tantangan kompetisi di antara para staf untuk berprestasi.
Tugas tim hanya menangani proses adminstratif dari berkas-berkas penelitian maupun
SK dari para staf.
Semestinya kita meniru langkah proses tersebut. Tetapi langkah ini sangat bergantung
pada wawasan para pejabat terkait. Selama ini bila ada orang mengalami keadaan
seperti Terry Mart kita akan cenderung menyalahkan yang bersangkutan dan memvonis
cuek. Kita yang umumnya mengurus dan membayar orang untuk proses kenaikan
pangkat nyaris tidak pernah menyalahkan para pejabat yang tidak kalah cueknya.
Secara filosofis, kenaikan pangkat sebenarnya merupakan penghargaan yang harus
diterima seseorang atas jerih payah serta prestasinya. Kita pun telah memilih ketua
jurusan, dekan, rektor dan para pembantunya. Mereka telah dikurangi jam mengajarnya,
diberi tempat ber-AC dan beberapa fasilitas termasuk gaji tambahan. Tetapi umumnya
mereka cuek atas sistem dan proses kenaikan pangkat di lingkungannya.
Hal yang juga perlu ditekankan adalah bahwa jenjang kepangkatan bukan sekedar
kebutuhan individu bersangkutan melainkan juga kebutuhan institusi. Salah satu jurusan
di PTN besar hendak membuka program S3. Dari nama staf pengajar yang tertera dalam
proposal terdapat dua doktor yang masih berstatus Asisten Ahli dan golongan 3A
dengan masa kerja delapan dan sepuluh tahun di golongan tersebut. Uniknya, di dalam
proposal keduanya ditulis berstatus lektor. Lagi-lagi cerita manipulasi. Padahal, salah
seorang staf jurusan tersebut yang juga tercatat sebagai salah seorang pengajar dalam
proposal adalah pembantu rektor.
Kasus di atas mengisaratkan ini bahwa para petinggi cuek, tak peduli dan mau
gampangnya saja. Mereka bangga dan puas misalnya dalam periode kepemimpinannya
berdiri program baru meskipun prosesnya melanggar aturan. Dus, peran dan tugas para
petinggi lembaga pendidikan harus diluruskan. Mereka pun harus diingatkan agar
berusaha menciptakan mekanisme birokrasi yang rasional dan memudahkan di
lembaganya masing-masing.
Urusan kenaikan pangkat harus dipermudah bahkan perlu dirombak secara lebih drastis
misalnya membuang beberapa persyaratan semisal pengabdian masyarakat. Sulit
dibayangkan bagaimana seorang seperti Jorga Ibrahim, DSc. yang berkutat dalam
kosmologi dan diferensial geometri harus mengabdi di masyarakat dalam arti
konvensional. Tuntutan ini tampak bagus tetapi mengabaikan pohon ilmu dan
perkembangannya. Akibatnya, persyaratan kenaikan pangkat menjadi kompleks, dunia
ilmu kita pun tidak mengalami kemajuan bahkan menampakkan kemunduran terlebih
bila dibanding negara tetangga. Persyaratan ini pun juga banyak menghasilkan guru
besar tanpa prestasi ilmiah yang berarti.
Mekanisme kenaikan pangkat otomatis asal persyaratan formal telah dipenuhi seperti di
salah satu fakultas di UGM perlu dicontoh. Apa salahnya bila Terry Mart di fisika UI,
Danny dan Permana di jurusan astronomi ITB naik pangkat otomatis dalam artian tidak
mengurus sendiri? Seperti ditulis Liek Wilardjo, Danny dan Permana cuek dengan
pangkatnya dan telah puas dengan pengakuan dalam bentuk lain yakni diundang dalam
seminar internasional. Kasus Permana dan peraih ITSF award Dr. Evvy Kartini adalah
kasus khusus yang tidak mestinya digeneralisir. Permana dan Evvy Kartini berasal dari
keluarga berada dan tidak ada masalah dengan gajinya yang tidak seberapa dan tidak
bertambah. Permana sanggup menyediakan dana sendiri untuk satu tahun pertama
studinya di Texas. Demikian pula Evvy Kartini ketika beberapa kali keluar negeri.
Cukup mendesak bagi lembaga pendidikan untuk berinisiatif membuat kebijakan dan
mekanisme kenaikan pangkat otomatis. Dengan demikian dosen yang gajinya sangat
mepet itu tak perlu lagi dibebani oleh banyak hal. Ironi departemen agama yang dikenal
sebagai lembaga paling korup tidak perlu diulangi dengan membuat departemen
pendidikan khususnya pendidikan tinggi sebagai lembaga paling tidak ilmiah.
Kita pun sepakat bahwa seunggul apapun suatu bibit tidak akan dapat tumbuh baik di
lahan yang tandus dan gersang. Melihat prestasi pelajar Indonesia ketika studi di luar
negeri maka tanpa keraguan sedikitpun kita berani mengatakan bahwa SDM kita setara
dan tidak kalah dari SDM negara manapun. Sayangnya, bibit-bibit yang telah diolah
sedemikian rupa di negeri maju itu sekembalinya di tanah air menjadi layu sebelum
berkembang. Mereka pun diperkosa sedemikian rupa sehingga akhirnya menjadi PSK,
Pekerja SKS Komersial yang mengajar di mana-mana dan tidak lagi mempunyai waktu
untuk riset bahkan sekedar belajar hal baru. Tragis memang, tetapi siapa peduli?
*) Pekerja LaFTiFA (Lab Fisika Teori dan Filsafat Alam) ITS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

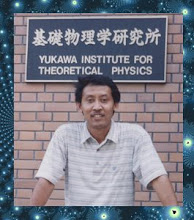
1 komentar:
Pak Terry sampai awal 2010 ini belum juga Guru Besar, terlalu sibuk dengan risetnya kali sehingga ga sempat ngurus jadi GB.
Posting Komentar