SURYA, 27 Juli 2004
Oleh: Agus Purwanto*)
Dalam rentang waktu satu tahun ini kita disodori tiga peristiwa serupa meski tak sama
yaitu Inul, AFI dan pilpres. Ketiganya merupakan jalan menuju puncak yang menyita
perhatian publik, fenomenal dan rakyat menjadi penentu akhirnya. Ketiganya juga
menyimpan ironi yakni melibatkan asing dan mengisyaratkan ketakberdayaan agama.
Kedaulatan Rakyat
Inul adalah pribadi yang melejit dengan gerak revolusi pinggulanya yang berkecepatan
tinggi. Ketika karir ini masih bersifat lokal yakni dari kampung ke kampung tidak
terdengar tanggapan atasnya. Tetapi begitu naik ke level nasional mulai muncul kritik
dan kontroversi. Kritik keras bahkan larangan atas Inul dan Inulisasi direpresentasikan
oleh raja dangdut, Rhoma Irama.
Sebenarnya kritik Rhoma ada pada jalur yang benar tetapi wajah sendu, polos dan
kadang tetes air mata Inul membangkitkan simpati massa atasnya dan anti Rhoma.
Singkat kata, Inul menang dan popularitasnya kian meroket. Banyak artis berdecak
kagum dan menumpang ketenarannya.
AFI adalah aktivitas kelompok yang mampu memaksa sebagian masyarakat duduk
manis di depan teve selama dua jam setiap Sabtu malam dan mendiskusikannya
keesokan harinya. Ada tiga juri yang menilai penampilan setiap kontestan AFI tetapi
kata akhir tereliminasi tidaknya sang kontestan adalah para pemirsa.
Pemenang akhir AFI pertama adalah Fery kontestan asal Medan. Penampilannya yang
kalem dan cerita yang sempat berkembang sebelumnya bahwa dia berasal dari kalangan
wong cilik telah menumbuhkan simpati dan mengalahkan dua pesaing akhirnya KIA
dan Mawar. Para pengamat dan pekerja seni seperti Agus Sutejo Jiwo di salah satu teve
swasta mengatakan bahwa sebenarnya KIA lebih representatif daripada Fery.
Pemilu 5 Juli merupakan hajatan nasional dengan berbagai suguhan baru yang sangat
menarik. Salah satu suguhan tersebut adalah debat capres, para capres bebas mengurai
argument, bersumpah dan menjanjikan berbagai layanan gratis bila terpilih. Tetapi
keputusan akhir pemenang pilpres adalah rakyat yang memutuskannya di 570 000-an
TPS di seluruh pelosok tanah air.
Pemenangnya adalah mereka yang simpatik, tinggi besar, tampan dan pandai menyanyi,
serta yang dianiaya dengan fatwa haram. Pasangan paling kredibel dan kompeten yang
konon didukung kelompok reformis maupun strong and democratic leader versi iklan
kampanye Gus Dur terpaksa harus tersingkir.
Kesamaan dari tiga peristiwa di atas adalah kedaulatan rakyat dan keterlibatan pihak
asing. Inul menang dari Rhoma, Fery menjadi nomor satu dan SBY-JK serta Mega-
Hasyim masuk pilpres putaran kedua adalah atas kehendak rakyat. Untuk kasus terakhir
kita perlu menyampaikan selamat kepada rakyat yang telah menentukan calon
pimpinannya lima tahun ke depan secara bebas dan mandiri. SELAMAT untuk rakyat.
Ketiganya juga melibatkan asing. Inul makin berkibar ketika media asing Newsweek
memberitakan perjalanan karirnya secara cukup lengkap. AFI, Indonesian Idol maupun
“Who Wants to Be a Millioner” adalah tayangan import atau produk asing. Sedangkan
pemilu saat ini juga didanai, ditongkrongi dan dipengaruhi orang asing yang berkedok
pengamat, analis maupun akademisi.
Kematian Agama
Ketiga peristiwa di atas juga mengisyaratkan satu hal yang perlu dicermati dan disikapi
lebih serius. Kuntowijoyo (Kompas, 7/7/2004) dalam kasus politik yang baru
berlangsung menyebut dengan istilah pragmatisme religius. Maksudnya, dikotomi
sekuler-religius hilang dan semua urusan mempunyai dimensi rasional, ketuhanan dan
kemanusiaan. Kunto merujuk fakta bahwa semua pasangan capres-cawapres membawa
warna nasionalis-religius.
Bila hanya melihat peristiwa politik pilpres kita mungkin memang harus optimis seperti
akhir tulisan Kunto, siapapun yang dipilih hasilnya pasti sekuler-religius. Namun
menjadi lain bila tiga peristiwa di atas dilihat sebagai satu kesatuan yang kronologis dan
hirarkis. Mulanya Inul sebagai individu, kemudian AFI sebagai komunitas panggung
Indosiar dan terakhir perhelatan nasional pilpres.
Inul berasal dari keluarga biasa yang cukup aktif dalam mengikuti pengajian di
Pasuruan salah satu kota santri di Jatim. Pasuruan sendiri sempat dua kali mencuri
perhatian publik tanah air. Tepatnya ketika Amien Rais dicekal datang di kota tersebut
beberapa tahun lalu, dan ketika fatwa haram memilih pemimpin perempuan tiga bulan
lalu.
Tetapi Inul dan Inulisasi yang berkembang pesat sama sekali tidak merepresentasikan
santri dan berbagai atributnya. Santri yang baru belajar mengeja huruf hijaiyah pun tahu
bahwa goyang ngebor Inul dilarang Islam untuk dipertontonkan. Uniknya, pemuda-
pemuda kampung yang cukup rajin sholat berjamaah di masjid ikut mencemooh Rhoma
Irama lantaran pernah memarahi Inul.
Di sini agama menjadi tidak berdaya menyentuh problem Inul dengan kreasinya. Opini
yang berkembang adalah goyang ngebor merupakan problem seni dan kreativitas
karenanya tidak perlu dilarang. Sesekali diberitakan bahwa Inul adalah alumni sekolah
islam dan pandai membaca al-Qur’an untuk membangun opini bahwa sang ratu ngebor
adalah sosok kreatif-religius.
Di akhir setiap acara AFI selalu ada peserta yang tereliminasi. Di saat perpisahan yang
mengharukan peserta selalu berangkulan satu sama lain sambil –maaf- mengelus-elus
pundak yang tak tertutup kain dan bercium pipi peserta tereliminasi yang lawan jenis
sekalipun. Beberapa menit menjelang acara berakhir ada nasihat dari pembina ruhani
AFI ,”Jangan lupa, rajin sembahyang.” AFI pun tampak bagai tontonan artistik-religius.
Artinya, seni dengan segala asesorisnya termasuk yang menabrak agama maupun
kegiatan ritual seperti sembayang dapat berjalan berbarengan secara damai.
Kasus pemilu mungkin yang paling seru. Para pemuka agama berdiri berseberangan,
saling hajar lalu minta dukungan pada komunitas yang sama. Mereka pun tanpa risih
membicarakan pembagian bakal pendapatan dengan rekan yang kebetulan lain
dukungannya. Padahal pembicaraan itu ditayangkan media elektronik secara luas. Gus
Dur pun terpaksa menjadi makelar dengan meminta orang lain menyoblos pasangan
Wiranto-Solah sementara dia sendiri mengulang-ulang pernyataan akan golput.
Ummat yang selama ini penurut dan patuh mulai berani mengabaikan pimpinan mereka
dan secara bebas menentukan calonnya sendiri. Ummat mulai “rasional” dan tidak takut
kuwalat karena tidak mengikuti saran dan ajakan para kyai. Lebih dari itu, ummat juga
tidak peduli isu “anti islam” yang dihembuskan pada calon pilihannya, pun tak peduli
fatwa haram presiden perempuan.
Peristiwa elit agama selama musim kampanye lalu mengingatkan kita atas perilaku para
agamawan di Eropa abad 19 yang tidak sesuai dengan kaidah agama yang banyak
dikhutbahkannya. Waktu itu Nietsczhe memberontak dengan teriakan terkenal, “Tuhan
telah mati”. Protes Nietsczhe cukup relevan diusung ke negeri ini. Inuliasasi, AFI dan
pemberontakan atas perilaku elit agama serta perilaku elit agama itu sendiri saat pilpres
tentu lebih dari sekedar fenomena sekuler-religius melainkan juga kebangkrutan dan
kecenderungan pada kematian agama.
Atau boleh juga meminjam istilah Comte, masyarakat Indonesia sedang memasuki
jaman ketiga yakni jaman positif. Jaman dengan segala fenomenanya yang tidak lagi
memerlukan penjelasan teologis (agama) maupun metafisis.
Menanti Kesadaran Elit Agama
Ketiga peristiwa di atas jelas memberi pesan yang memprihatinkan dari perspektif
agama. Jepang barangkali dapat dijadikan contoh dari negeri positivistik. Di bulan
Desember denyut perayaan Natal dapat dirasakan di seantero Jepang. Uniknya, mereka
tidak merasa atau mengaku sebagai umat kristiani. Mereka pun mengaku tidak tahu
mengapa harus merayakan Natal selain tahu bahwa Barat melakukan pesta semacam ini
di setiap akhir tahun. Dalam banyak kesempatan penulis bertanya kepada mahasiswa S1
sampai S3 perihal agama mereka. Jawabnya seragam,”tidak tahu” dan mereka merasa
tidak beragama, dan mengalami peristiwa keagamaan hanya dalam tiga kesempatan.
Ketika lahir disambut secara budhis, menikah secara kristiani dan kembali budhis dalam
ritual kematian.
Ketercerabutan cita keagamaan masyarakat Indonesia belum separah masyarakat Jepang.
Namun bila melihat ke belakang misalnya sepuluh tahun lalu kemudian dibandingkan
keadaan saat ini, yang mana perempuan Indonesia berani tampil semi telanjang di
televisi tanpa rasa risih sedikit pun maka tidak terlalu berlebihan bila dibayangkan dan
diprediksi bahwa dalam satu-dua dasawarsa ke depan kita akan lebih dari Jepang dalam
pengasingan agama secara formal dan lebih dari Barat dalam memuja tradisi nudis dan
pergaulan bebas.
Kematian agama tidak berarti ateisme yang meniadakan Tuhan melainkan
dikesampingkannya peran agama dan Tuhan sebagaimana pandangan dunia mekanik
(mechanical world view). Tuhan dan ciptaanNya diibaratkan sebagai clockmaker dan
jam yang dibuatnya. Mulanya sang pembuat jam berfikir keras jam macam apa yang
akan dibuatnya, setelah ide muncul jam pun dibuat dan kemudian dibiarkan berjalan
sendiri sampai rusak. Singkatnya, Tuhan telah pensiun dari kesibukan proses penciptaan
mahluk.
Dalam era kematian agama barangkali Tuhan masih disebut-sebut bahkan secara hiruk-
pikuk. Namun penyebutan itu telah kehilangan makna transendentalnya. Penyebutan itu
pun tak lebih dari sekedar menyebut-nyebut perihal jenazah yang ada di depan kita
sementara kita bebas melakukan apa saja tanpa segan dan malu di depannya.
Itulah gambaran keagamaan masyarakat Indonesia yang terefleksi dari tiga serangkai
peristiwa Inul, AFI dan pilpres. Para elit harus membumikan ajaran agama dan tidak
boleh memperdagangkan dan mempermainkan agama. Elit Muhammadiyah, NU, Persis,
al-Irsyad dan yang lainnya tidak boleh gampang dibeli. Aktifis HMI, PMII, IMM,
KAMMI dan berbagai kelompok pengajian kampus tidak boleh disewa untuk demo
ataupun berebut duduk di belakang saat ujian apalagi nyontek. Sedikit kesalahan mereka
akan mempercepat proses kematian agama di negeri ini. Sebab merekalah simbol dan
bukti doktrin agama terdekat yang dapat dilihat langsung massa kebanyakan.
*) Pekerja di Lab Fisika Teori dan Filsafat Alam (LaFTiFA) ITS; mantan Vice-
President of Saijou-Hiroshima Association.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

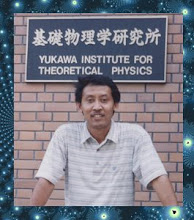
Tidak ada komentar:
Posting Komentar