SURYA, 17 Juli 2003
Oleh: Agus Purwanto*)
Kejutan muncul lagi dari dunia pendidikan. Kejutan terbaru itu adalah
kebijakan tingginya biaya yang harus disiapkan calon mahasiswa baru
beberapa PTN terkenal. Kebijakan paradoks sebab selain terjadi di saat krisis
ekonomi berkepanjangan dan jumlah penduduk miskin meningkat, juga lahir
saat pemerintah berkuasa merupakan representasi dari kawula alit. Mengingat
seringnya kejutan dunia pendidikan ada baiknya kita coba memahami sebab
mendasarnya.
Harapan dan Impian
Kejatuhan Suharto tahun 1998 menumbuhkan harapan baru akan perubahan
mendasar setelah bertahun-tahun hidup dalam keadaan tertekan. Isu
desentralisasi dan otonomi daerah pun bergulir dan lahirlah UU otonomi yang
di dalamnya memuat kebijakan otonomi perguruan tinggi (PT). Masyarakat
menyambut antusias kebijakan ini apalagi yang dipilih menjadi percontohan
adalah empat PT impian yakni UGM, UI, ITB dan IPB.
Masyarakat membayangkan dapat masuk PT tersebut dengan biaya lebih
murah dan dapat menikmati pendidikan yang lebih bermutu.
Pertimbangannya, PT tersebut mampu mencari dan mengelola dana sendiri
serta menentukan perkuliahan tanpa banyak titipan dan campur tangan dari
pemerintah. Harapan yang tidak berlebihan mengingat empat PTN tersebut
merupakan PTN tertua, besar dan mapan. Alumninya tersebar di mana-mana,
ada yang menjadi pengusaha besar dan sebagian lainnya menempati pos-pos
penting pemerintahan. Jaringannya yang luas memungkinkan penggalian
dana alternatif untuk biaya operasionalnya.
Kalangan akademisi pun menaruh harapan besar pada perubahan pengelolaan
PT ke dalam Badan Hukum Milik Negara (BHMN) ini. Sebagian mereka
berharap profesionalisme khususnya dalam riset dapat mengalami perubahan
dan kemajuan yang signifikan. Sebabnya mereka akan dibayar sesuai
prestasinya; yang berprestasi dihargai tinggi dan sebaliknya bagi yang tidak
bahkan posisinya sebagai staf akademik akan ditinjau ulang. Dus, kompetisi
dalam riset dapat berlangsung dan the real university sebagai research centre
bukan lagi hayalan tetapi akan segera terealiasi.
Gebrakan awal dilakukan oleh ITB dengan memberi opsi kerja di luar dan
berhenti dari ITB atau tetap di ITB dan tidak nyambi di luar. Keluarnya ahli
teknologi informasi (IT) Dr. Onno W. Purbo dari ITB dan memilih
mengembangkan IT di luar tembok akademik adalah contoh yang fenomenal
dan meneguhkan harapan di atas. ITB juga akan melakukan evaluasi bagi staf
akademiknya apakah memenuhi kualifikasi sebagai periset, hanya sebagai
pengajar atau bahkan melorot sebagai staf administrasi.
PTN lain juga merespon penetapan UGM, UI, ITB dan IPB menjadi BHMN.
Mereka berbenah agar dapat memenuhi kualifikasi dan layak diberi status
BHMN. Alasannya adalah prestise, hanya PTN yang dinilai mandiri saja yang
memenuhi kualifikasi BHMN atau dengan kata lain PTN non BHMN adalah
PTN belum mapan dan belum mandiri.
Potret Riel PT
Masyarakat shock dan bertanya-tanya ketika kebijakan realisasi PT otonom
keluar. Impian mereka pun buyar. Biaya yang harus disiapkan para calon
mahasiswa jauh di luar jangkauan mereka. Masyarakat faham bahwa
pendidikan itu mahal, mereka pun mengerti alasan mengapa hanya empat PTN
yang dipandang mampu mengatasi tingginya biaya pendidikan tersebut. Tetapi
penanggulangan dengan memungut biaya tinggi dari calon mahasiswa
tentunya dapat dilakukan oleh semua PTN bukan hanya UGM, UI, ITB dan
IPB.
Pertanyaannya, apa maksud pemerintah memilih empat PTN di atas sebagai
percontohan PTN otonomi? Mungkinkan pemerintah telah salah perhitungan
dan mengira bahwa keempat PTN tersebut kokoh dan mapan tetapi
sebenarnya rapuh dan keropos? Atau, apa sebenarnya yang terjadi pada para
elit baik elit politik, ekonomi maupun elit pendidikan bangsa ini?
Para akademisi sering melakukan pembelaan bahwa PT tidak berkembang
menjadi lembaga riset adalah akibat minimnya dana. Tetapi seperti telah
penulis uraikan (Surya, 19/7/2002), dana bukanlah sebab utama. Motivasi dan
kemampuan proper research staf akademik itu sendiri baik yang telah bergelar
doktor maupun guru besar itulah biang keroknya. Sikap dan perilaku
mahasiswa Indonesia yang di luar negeri membuktikan hal tersebut. Fasilitas
yang lengkap dan beasiswa yang cukup tidak banyak memperbaiki prestasi
mereka dalam riset.
Kondisi di atas direkam dengan baik oleh Ismail Raji al-Faruqi di dalam
bukunya Islamization of Knowledge. Al-Faruqi memberi contoh seorang dosen
universitas negara berkembang bergelar profesor yang meraih gelar doktor di
negara Barat. Ia mendapat pendidikan di sana dan lulus dengan nilai dan
prestasi sedang. Ia menuntut ilmu dengan motivasi rendah dan tidak
mendapatkan semua ilmu yang bisa diperolehnya di sana. Ia merasa cukup
puas untuk lulus, mendapat gelar, kembali ke negeri asalnya, dan
mendapatkan posisi penting serta menguntungkan. Buku-buku yang dibacanya
ketika masih kuliah adalah puncak pengetahuannya, karena kini ia tidak
memiliki waktu, tenaga, dan motivasi untuk mendobrak batas pengetahuan
yang dimilikinya.
Kegagalan Pendidikan
Ketetapan biaya masuk PTN sangat mahal adalah jalan pintas untuk
mengatasi tingginya biaya operasional pendidikan. Hal ini dapat dipandang
sebagai cerminan sikap malas, tidak kreatif dan rendahnya dedikasi para elit
dan pengelola pendidikan kita. Dedikasi rendah ini pula yang menyebabkan PT
kita sekedar menjadi lembaga pengajaran yang monoton dan rutin, bukan
lembaga riset. Kenyataan tersebut juga mengisyaratkan PT kita bahkan yang
paling top sekalipun ternyata rapuh dan keropos.
Selanjutnya, kita pun dapat memahami peristiwa penting lainnya. Tiga
dasawarsa lalu, Malaysia mengirim banyak mahasiswa ke Indonesia dan
mendatangkan tenaga pengajar kita ke sana. Mereka merasa tertinggal dari
kita dan kemudian membuat kebijakan untuk mengejar ketertinggalan
tersebut. Hasilnya, Malaysia melejit meninggalkan kita dalam pendidikan dan
kini kita menjadikan negeri jiran tersebut sebagai tempat alternatif studi
lanjut. Kenyataan terakhir memperlihatkan bahwa pendidikan kita juga
ketinggalan dari Vietnam yang baru selesai perang melawan Amerika di tahun
1970-an. Pertanyaannya, apa yang dilakukan para akademisi selama ini
sehingga mengalami kemunduran ?
Kegagalan di atas dapat dijabarkan lebih lanjut dengan melihat dua kasus
sangat menyolok dan mempunyai implikasi luas yakni pendidikan moral dan
agama. Selama hampir tiga dasawarsa pendidikan kita sejak SD sampai PT
memisahkan pendidikan moral dan agama. Keduanya diberikan secara
terpisah oleh para pengajar yang berbeda dan berasal dari “lingkungan” yang
berbeda pula.
Hasilnya sangat mengesankan, beberapa kali survey memperlihatkan bahwa
Indonesia menduduki top rank dunia dalam hal korupsi dan hutang luar negeri.
Padahal kegiatan keagamaan bahkan di sekolah-sekolah pun terus bertambah.
Produk terbaru DPR yakni UU Pilpres adalah salah satu contoh lain ironi hasil
pendidikan kita. Anggota dewan yang terhormat yang umumnya sudah
mengenyam pendidikan tinggi dan digaji tinggi itu ternyata sikap dan
dedikasinya lumayan payah.
Pasca UU Sisdiknas
Penyakit akut korupsi telah merambah ke mana-mana termasuk di lembaga
pendidikan. PT terus melengkapi sarana dan prasarananya termasuk
gedung-gedung pertemuan yang representatif. Sumber dana PT di antaranya
adalah pemerintah pusat, Iuran Orang Tua Mahasiswa (IOM) maupun
pinjaman dari bank dan luar negeri lainnya. Di dalam proses melengkapi atau
membangun sarana dan prasarana sering terdengar berita penyimpangan dana
proyek.
Selain itu, meskipun gedung pertemuan megah telah dibangun, pertemuan
semisal membahas proposal penelitian ataupun rapat materi kurikulum masih
banyak dilakukan di hotel mewah di luar kota. Di akhir tahun ajaran tidak
jarang para staf yang umumnya sudah hidup relatif cukup, karyawan serta
keluarganya rekreasi beberapa hari dengan biaya instansi. Padahal mereka
tahu bahwa fasilitas institusinya masih jauh dari lengkap, tidak sedikit dari
mahasiswanya yang kesulitan dan tertunda membayar SPP ataupun IOM.
Sebab utama berbagai persoalan di tanah air adalah krismon, krisis moral dan
nurani. Lantaran penyebab tersebut berada di wilayah internal ruang batin
maka berbagai peraturan dan hukum tidak sanggup menjerat para pelaku
kejahatan kecuali yang tidak berpendidikan. Dalam perspektif ini pendidikan
bagi sebagian orang justru menjadi proses pencanggihan kejahatan sedemikian
rupa sehingga sulit dijerat oleh jaring hukum formal.
Karena itu, persoalan serius setelah pendidikan agama masuk ke dalam UU
Sisdiknas yaitu bagaimana menjadikan agama sebagai ruh dan bukan sekedar
asesoris pendidikan. Bagaimana menjadikan agama sebagai perekat dan bukan
pemicu masalah dan konflik baik antar pemeluk agama yang sama maupun
yang berbeda. Dari perspektif agama aneka paradoks di negeri ini termasuk
paradoks dunia pendidikan dapat dikatakan sebagai kegagalan pendidikan
agama. Pengajaran agama di sekolah justru melahirkan sekularisasi. Khusyuk
di ruang ibadah tetapi culas di luar, relijius dalam penampilan fisik tetapi
sangat materialis pikiran dan tindakannya.
Untuk itu ada baiknya merenungkan pernyataan Thomas Merton di dalam
Misticism in the Nuclear Age-nya.”Anda tidak bisa mengubah dunia hanya
dengan sebuah sistem, Anda tidak bisa meciptakan kedamaian tanpa
kedermawanan, dan Anda tidak bisa menciptakan keteraturan sosial tanpa
melibatkan orang-orang suci, kaum mistis dan para nabi”. Dus, penyelesaian
atas berbagai keruwetan di negeri ini termasuk di dunia pendidikannya harus
diawali dengan kebersihan dan kesucian, moralitas.
Ada kehidupan Nabi saw yang harus ditiru khususnya oleh para elit politik,
ekonomi, agama maupun pendidikan dari negeri yang mayoritas muslim ini.
Sebagai pemimpin Nabi saw tidak melarang umatnya kaya tetapi beliau sendiri
hidup dalam keadaan serba kekurangan. Nabi tidak berebut materi dengan
umat yang dipimpinnya atas nama dana operasional pendidikan, pengkaderan
dan perjuangan dakwah, dana rekreasi, atau dana pertemuan di tempat mewah
di luar kota. Pendidikan akan efektif bila dibarengi keteladanan.
*) Pekerja di LaFTiFA (Lab Fisika Teori dan Filsafat Alam) ITS.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

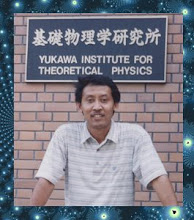
Tidak ada komentar:
Posting Komentar