SURYA, 19 Juli 2002
Oleh: Agus Purwanto *)
Artikel Prof. Dr. Ir. Hendrawan Soetanto (HS) dengan judul “Lima kegagalan tugas guru besar” di harian ini 27 Juni 2002 lalu isinya cukup menggelitik. Betapa tidak, dari delapan tugas guru besar ternyata lima diantaranya gagal dilaksanakan. Hal yang membuat kita tercengang bukan sekedar lima dari jumlah yang delapan. Dari artikel tersebut kita dapatkan bahwa kegagalan
para guru besar justru ada pada tugas yang mendasar sedangkan tiga yang berhasil adalah tugas sekunder seperti mengajar, pelayanan pada universitas, dan mengabdi di luar universitas. Lima kegagalannya adalah dalam pelaksanaan tugas sebagai mentor, penemu sesuatu yang baru, penulis publikasi ilmiah, penyebarluas kebenaran ilmiah, dan pelaku perubahan.
Di dalam artikel kali ini penulis memberi catatan lebih lanjut pada isi tulisan tersebut. Penulis mencoba melacak sebab-sebab mengapa kegagalan itu terjadi. Selanjutnya menawarkan solusi sederhana namun cukup efektif untuk jangka panjang.
Tradisi yang hilang
Ketika masih mahasiswa penulis merasakan ada sesuatu yang kurang di perguruan tinggi. Sesuatu tersebut adalah hal yang penulis impikan sebelum menjadi mahasiswa yaitu tradisi berdiskusi ilmiah atau berfikir bebas. Mahasiswa cenderung hidup sebagai anak manis yang malas berfikir tentang apa yang dijejalkan di dalam kelas apalagi berfikir dan mensikapi keadaan
sekitarnya secara kritis.
Keadaan di atas wajar terjadi bila menilik hasil pengamatan Prof. HS di atas. Beberapa tahun lalu para kolega penulis ngrasani dan mengeluhkan mahasiswa karena tidak mau me-review serta memahami lebih lanjut materi kuliah. Saat itu penulis mengingatkan akan adanya hukum asimilasi. Hukum tersebut kurang lebih menyatakan bahwa pohon mangga tentu akan berbuah mangga pula bukan yang lain. Artinya, kondisi mahasiswa yang memprihatinkan bisa dilacak sebab musababnya pada kualitas pohonnya dalam hal ini gurunya.
Kenyataannya, tradisi diskusi ilmiah bukan saja hilang dari kehidupan mahasiswa melainkan juga dari para gurunya itu sendiri. Artinya dunia universitas memang mengalami krisis dan butuh simbol. Simbol yang dimaksud adalah staf pengajar yang mempunyai moralitas dan reputasi berupa karya ilmiah yang diakui komunitas sejenis secara luas. Tiadanya tradisi berfikir bebas dan miskinnya prestasi publikasi adalah kenyataan pahit yang sulit disangkal. Pertanyaannya mengapa kondisi ini bisa terjadi.
Sebab klasiknya adalah gaji rendah dan keterbatasan fasilitas laboratorium dan perpustakaan. Gaji rendah memaksa para staf pengajar harus kerja sambilan. Seringkali jenis kerja sambilannya tidak terkait dengan bidang yang digelutinya secara formal dan jam kerja sambilannya melebihi jam kerja resminya. Sebab berikutnya adalah minimnya fasilitas laboratorium dan perpustakaan.
Kedua alasan tersebut cukup masuk akal meskipun bila dikritisi lebih lanjut akan terasa janggal dan karenanya perlu kita pertanyakan keabsahannya. Mengapa janggal ? Benarkah sebab utamanya adalah gaji dan fasilitas?
Gaji kecil merupakan cerita lama dan terwariskan secara turun temurun. Dengan demikian orang yang membuat pilihan profesi sebagai staf akademik di perguruan tinggi mestinya sadar bahwa gajinya akan kecil. Kesadaran ini akan memaksanya berfikir alternatif agar bisa eksis sebagai komunitas universitas dengan segala misi sucinya. Kenyataannya, gaji kecil seolah-olah
merupakan kebijakan yang baru diterapkan setelah sebelumnya bergaji besar yang karenanya merasa absah untuk shock berkepanjangan dan tak peduli atas misi universitas.
Fasilitas laboratorium dan perpustakaan yang tidak memadai juga sudah diketahui oleh para staf sejak masih menjadi mahasiswa. Karenanya kenyataan ini juga harus diantisipasi jauh-jauh hari sebelumnya dalam bentuk perencanaan pengembangan. Misalnya, dalam dua-tiga kali kurun lima tahunan laboratorium sudah mempunyai peralatan demi peralatan selanjutnya bisa riset dan karenanya menghasilkan paten atau publikasi di jurnal internasional.
Itulah kejanggalan yang penulis maksudkan yaitu para staf seolah-olah tidak sadar kondisi gaji dan laboratoriumnya. Namun menurut hemat penulis keduanya bukanlah alasan utama bagi para staf akademik universitas terlebih para guru besarnya untuk tidak berkarya dan menjalankan misi pencerahan dan perubahan sosial. Bila demikian apa alasan mendasar atas tiadanya prestasi tersebut?
Tradisi yang tinggal impian
Penulis pernah membayangkan betapa indahnya bila bisa studi di luar negeri. Di sana penulis akan bertemu dengan para mahaguru yang terkenal. Selain itu juga bisa mengadakan diskusi ilmiah dan debat bebas dengan para duta bangsa pilihan yang berasal dari berbagai instansi di tanah air. Impian penulis studi di luar negeri, bertemu dan berguru kepada para mahaguru yang
sangat piawai di bidangnya menjadi kenyataan. Meskipun demikian ada juga impian yang tinggal impian dan membuat masygul.
Curiosity “ilmuwan” kita di luar negeri ternyata relatif rendah. Hal ini bisa dilihat dari jenis aktifitas yang diselengarakan oleh organisasi PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) maupun isi mailing list-nya. Berbeda dengan kegiatan olah raga yang umumnya diselenggarakan setiap hari Sabtu dan atau hari Minggu, kegiatan diskusi atau presentasi sangat jarang diselenggarakan.
Mahasiswa kita di luar negeri umumnya hidup dengan beasiswa berlebih meski membawa keluarga sekalipun. Fasilitas laboratorium dan perpustakaan sangat lengkap. Pendeknya mahasiswa tinggal melakukan riset yang sesuai minatnya tanpa harus memikirkan kondisi dapurnya. Di Jepang yang menerapkan sistem pendidikan lanjut by research umumnya menuntut dua atau tiga published paper sebagai syarat minimum untuk mendapatkan gelar doktor. Waktu total studi tingkat doktor tiga tahun. Rentang waktu ini ditambah satu tahun sebagai research student cukup untuk menulis publikasilebih dari jumlah minimum sekaligus memilih jurnal dengan impact factor tinggi yang proses reviewnya memerlukan waktu lebih lama.
Namun yang kita saksikan semua kondisi itu belum termanfaatkan secara maksimal. Tidak sedikit dari pelajar Indonesia di luar negeri yang sebagian dari mereka adalah staf perguruan tinggi ini terseok-seok dan molor masa studinya. Mereka bak anak ayam mati di lumbung padi. Memang orang-orang pilihan ini akhirnya lulus dan menyandang gelar doktor meski sebagai minimalis yakni lulus dengan publikasi di jurnal ber-impact factor rendah dan dalam jumlah yang minim pula.
Jelaslah alasan mendasar atas gagalnya tugas yang diemban oleh guru besar khususnya dan para staf bergelar doktor umumnya bukannya gaji kecil dan keterbatasan fasilitas. Sebab utamanya adalah motivasi dan kemampuan proper research para doktor dan guru besar itu sendiri. Dari ungkapan polos ataupun yang sedikit dikemas dapat kita tangkap bahwa misi utama studi lanjut kebanyakan para duta bangsa tersebut adalah gelar itu sendiri.
Keadaan di atas sangat terkait dengan budaya malu. Fenomena gelar doktor yang didapat hanya dengan membayar beberapa juta adalah fenomena masyarakat yang kehilangan rasa malu. Demikian juga fenomena doktor dan guru besar tanpa karya yang dibuktikan melalui paten atau publikasi di jurnal internasional. Kondisi tersebut diperparah kenyataan bahwa masyarakat tidak bisa mengontrol mereka. Siapa di antara mereka yang memang ilmuwan sejati dan siapa yang ilmuwan gadungan atau pseudoscientist. Bila demikian akar masalahnya bagaimana cara mengatasi hal tersebut?
Ada cara yang cukup efektif untuk menumbuhkan budaya malu dan pada gilirannya memaksa para akademisi berkarya atau setidaknya diam bila tidak mempunyai karya. Dengan demikian atmosfer dunia ilmu kita akan terbebas dari polusi kebohongan atau klaim-klaim kosong. Cara tersebut adalah membuat situs yang berisi data anggota komunitas akademik tertentu lengkap
dengan daftar publikasinya. Cara ini sudah diterapkan oleh komunitas fisika Indonesia khususnya komunitas fisikawan teoritiknya sejak tahun 1997. Situs tersebut adalah http://hfi.fisika.net atau http://gfti.fisika.net.
Di situs kedua, keanggotaan diklasifikasikan menjadi dua yakni honorary dan regular member. Anggota kehormatan (honorary) adalah anggota baik profesor, doktor, master atau sarjana fisika teoritik yang belum mempunyai publikasi internasional. Sedangkan anggota biasa adalah mereka yang mempunyai sedikitnya satu publikasi di jurnal internasional. Situs ini disambungkan ke database milik Los Alamos National Laboratory USA dan Yukawa Institute for Theoretical Physics Kyoto Jepang. Karenanya, data publikasi akan segera muncul di situs GFTI begitu data tersebut masuk di database dan muncul di situs kedua institusi tersebut.
Setiap orang bisa ngecek langsung nama-nama fisikawan teoritis kita yang pernah didengarnya. Apakah benar nama tersebut adalah ilmuwan hebat yang mempunyai karya atau sekedar ngetop karena di-blow up media massa. Jujur saja, barometer kerja seorang ilmuwan (eksakta khususnya) hanya dua yaitu paten atau publikasi di jurnal internasional. Pekerjaan seperti penataran atau menjadi pembicara pada berbagai seminar juga penting tetapi bukan yang utama.
Teknologi internet ini juga memungkinkan orang di seluruh dunia melacak kontribusi ilmuwan setiap negara termasuk Indonesia. Dengan demikian cepat atau lambat jati diri universitas kita yang sesungguhnya pun akan diketahui pula. Orang akan tahu apakah universitas kita adalah lembaga riset dengan karya-karya orisinil atau sekedar museum tempat menyimpan piranti laboratorium dan buku usang serta para staf pengajar dengan pengetahuan yang kadaluwarsa (berasal dari textbooks bukan jurnal terbaru) pula.
Penulis sendiri sampai pada kesimpulan bahwa universitas kita memang telah bermetamorfosis menjadi museum. Menyedihkan memang, tetapi apa boleh buat itulah realitas yang harus terlebih dulu kita akui baru kemudian berusaha mengatasinya. Itupun bila kita memang menghendaki. Sebab tidak tertutup kemungkinan kita lebih menyukai profesi sebagai penjaga museum ketimbang sebagai periset yang sekaligus agen pencerahan dan perubahan. Wallahua’lam.
*) Staf pengajar salah satu PTN di Jawa Timur, alumnus Universitas
Hiroshima
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

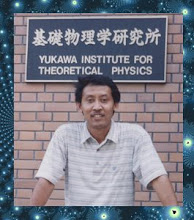
Tidak ada komentar:
Posting Komentar